Berita Jogja Hari Ini
Bagaimana Tumpukan Sampah di Yogyakarta Bisa Sebabkan Perubahan Iklim?
Secara teori, jika ada penumpukan sampah secara besar-besaran, daerah yang di bawah (tumpukan) akan mengalami kekurangan oksigen. Ketika kekurangan ok
Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Di tengah pesona wisata dan budaya Yogyakarta yang menawan, daerah ini menghadapi masalah krusial yang belum menemukan titik keseimbangan, yakni pengelolaan sampah.
Meskipun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilah sampah mulai meningkat, implementasinya masih jauh dari harapan.
Di sisi lain, pemerintah belum mampu menyediakan fasilitas pembuangan sampah yang berkelanjutan, menciptakan lingkaran setan yang semakin memperparah kondisi lingkungan.
Tantangan ini tidak hanya mengancam keindahan kota, tetapi juga kesehatan dan kelestarian ekosistem lokal.
Baca juga: Darurat Sampah di Jogja, Pakar UGM Sebut Penanganan di Hulu Harus Diperbaiki
Tumpukan sampah yang ada di DI Yogyakarta disebut-sebut bisa menyebabkan perubahan iklim.
Hal ini dijabarkan oleh Prof. Chandra Wahyu Purnomo, Dosen Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, pekan lalu.
“Secara teori, jika ada penumpukan sampah secara besar-besaran, daerah yang di bawah (tumpukan) akan mengalami kekurangan oksigen. Ketika kekurangan oksigen, bakteri anaerob akan bekerja di situ, mengurai organiknya, sehingga muncul CH4 atau metana,” jelas Chandra kepada Tribun Jogja.
Dia mengatakan, gas metana itu memiliki daya 40 kali lebih kuat untuk membentuk efek rumah kaca dibanding CO2 atau karbon dioksida.
“Jadi, gas metana ini, dibanding membakar batu bara, membakar kayu yang mengeluarkan CO2, dia punya efek lebih kuat untuk menciptakan efek rumah kaca,” paparnya.
Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer.
Perubahan itu menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna, keluar atmosfer.
Sinar matahari yang terlalu lama ada di bumi bisa menyebabkan kerusakan ekosistem, bahkan pencairan es di kutub-kutub. Mau tak mau, secara berurutan, iklim akan berubah dan mengakibatkan bencana maupun hal buruk lain.
“Sebenarnya, kita bisa keluar dari (permasalahan) itu. Kita coba lakukan seperti yang ada di TPA Jatibarang, Semarang bagaimana gas metana dari sampah itu bisa dikonversikan jadi listrik. Jadi, gas metana-nya jangan dilepas, tapi sekarang kan rata-rata dilepas gitu saja,” ucap Chandra.
Dia mengungkap, tumpukan sampah, yang juga ada di DIY bisa saja menyumbang 20 persen kontribusi efek rumah kaca.
Ini menjadi angka yang cukup besar, mengingat Indonesia juga akan mengalami dampaknya ketika bumi sedang mengalami perubahan iklim.
“Kalau berbicara Indonesia, yang paling besar (menciptakan efek rumah kaca) adalah perubahan tata ruang ya. Misalnya, ada hutan jadi pemukiman atau ada hutan jadi Ibu Kota Nusantara (IKN),” bebernya.
“Itu namanya Afolu atau Agriculture, Forestry and Other Land Use. Itu bisa berdampak sampai 60 persen dan menjadi perubahan iklim. Kemudian, 30 persennya dari energi, misal PLTU membakar batu bara, 20 persen ini dari tumpukan sampah dan 20 persennya lain-lain,” terang dia lagi.
Dengan adanya sampah yang menumpuk itu, Chandra mengingatkan kembali dengan kasus yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005.
Kala itu, TPA Leuwigajah meledak, longsoran sampah menimpa dua desa di Cimahi, yakni Cilimus dan Pojok, menewaskan 157 orang.
TPA Leuwigajah itu masih menggunakan sistem open dumping. Tengah malam, TPA itu diguyur hujan deras.
Akibatnya, konsentrasi gas metana dalam tumpukan sampah meningkat sehingga gunungan sampah sepanjang 200 meter dan setinggi 60 meter di TPA Leuwigajah runtuh dan diikuti suara gemuruh besar, bahkan terdengar hingga radius 10 kilometer.
Ribuan ton sampah terjun bebas dan menghantam dua permukiman penduduk yang berada di bawah TPA Leuwigajah.
Ratusan warga Kampung Cilimus dan Kampung Pojok pun tak sempat menyelamatkan diri dan terkubur bersama ribuan ton sampah tersebut.
“Karena Leuwigajah itu, kita jadi punya Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati setiap 21 Februari. Hari Sampah kita sudah punya, tapi ya masih gini-gini saja,” katanya.
Status Darurat Sampah DIY
Dikatakannya, penerapan status darurat sampah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) nilai belum mampu menurunkan tingkat produksi sampah di masyarakat.
Ia menilai keberanian Pemda DIY menutup Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan tidak dibarengi dengan penguatan sisi tengah dalam sistem pengelolaan sampah.
“Dari produsen, sampah seharusnya diolah dan dipilah di Tempat Pembuatan Sementara (TPS), TPS3R, maupun Bank Sampah (Waste Bank). Sebelum akhirnya masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” paparnya.
Kondisi diperkuat dengan masih rendahnya literasi pemilahan sampah di masyarakat, sehingga mereka menjadikan bagian tengah ini sebagai tempat pembuangan sampah utama.
Demikian juga dengan belum tersedianya tempat pengelolaan sampah utama, selepas TPST Piyungan ditutup menjadi sampah menghadirkan krisis lingkungan dinyatakan berstatus darurat sampah.
“Meski berstatus darurat, namun jumlah sampah yang dibuang masyarakat tidak berkurang. Bahkan muncul sejumlah titik yang dijadikan tempat pembuangan ilegal,” ucapnya.
Chandra menyatakan penyelesaian persoalan sampah di Yogyakarta harus dibagi dalam tiga tahap.
Dalam jangka pendek, Pemda DIY diminta untuk mengaktifkan bank sampah maupun TPS3R yang jumlahnya ratusan dan mayoritas dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).
“Di Sleman saja ada 30 TPS3R yang dibangun KemenPUPR senilai Rp600 juta namun mangkrak. Hanya 10 saja yang beroperasi. Aktifnya TPS3R ini baik di Sleman, Kota Yogyakarta maupun Bantul akan berdampak pada cepatnya proses pemilahan sampah,” terang koordinator Indonesia Solid Waste Forum (ISWF) itu.
Jangka menengah yaitu menyiapkan teknologi pengelolaan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) yang menghasilkan bahan bakar secara matang.
Dimana bahan bakar yang dihasilkan bisa dipergunakan industri sekitar sehingga meminimalkan biaya pengiriman dibandingkan ke luar provinsi.
Terakhir, jangka panjangnya adalah menyiapkan pusat pengelolaan besar berkapasitas minimal 500 ton per hari.
Langkah ini perlu didukung hadirnya kesimbangan kebijakan desentralisasi yang diterapkan sekarang dengan sentralisasi.
“Daerah menyiapkan tempat pengelolaan sampah sendiri. Sedangkan tempat pengelolaan besar yang dikelola Pemda DIY sebagai cadangan jika tempat pengelolaan di kabupaten/kota tidak berfungsi,” lanjutnya. (ard)
| Cara Lapor Jika Terjadi Kekerasan Anak dan Perempuan di Yogyakarta, Gratis Bebas Pulsa |

|
|---|
| Kronologi Kasus Dugaan Monopoli BBM oleh Oknum Polairud di Pantai Sadeng Gunungkidul |

|
|---|
| Mengenal Class Action, Cara Menuntut Pemerintah karena Kasus Keracunan MBG |

|
|---|
| Komentar Sri Sultan HB X soal Keracunan MBG di Jogja dan Sanksi untuk SPPG Menurut Undang-Undang |

|
|---|
| Kronologi Wisatawan asal Jakarta Hilang di Pantai Siung, Jenazah Ditemukan di Pantai Krakal |

|
|---|






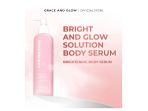







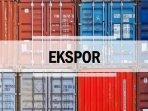

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.