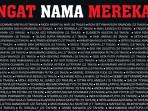Kisah Murkanya Dewa Krincingwesi dan Terbentuknya Merapi Sebagai Kraton Makhluk Halus
Alam pikiran tradisional masyarakat sekitar lereng Merapi memang sarat dengan mitos, dongeng, atau legenda yang beraneka nuansa dan versi
TRIBUNJOGJA.com, SLEMAN - Gunung Merapi mbledhos (meletus), itu barang lumrah.
Tapi bencana dengan korban puluhan jiwa akibat amukannya pada Selasa Kliwon 22 November 1994 seperti hendak merobek kesadaran manusia untuk berpikir realistis.
Betapapun "saktinya", mitos yang selama ini kuat diyakini penduduk di lerengnya tak mampu membendung dahsyatnya kekuatan fenomena alam.
Kendati begitu, sebuah mitos, dongeng, atau legenda kadang tidak serta merta harus dipandang sebelah mata begitu saja.
Hari itu langit cerah. Supiyem (39) seperti biasa berangkat ke hutan mencari rumput untuk sapi-sapinya.
Ketika sedang asyik menyabiti rumput, tiba-tiba langit mendung. Keranjang belum penuh terisi rumput ketika langit di atasnya berubah gelap.
Gumpalan-gumpalan awan coklat kehitaman bergulung-gulung berarak ke timur terbawa angin. Namun awan gelap itu mendadak balik kanan terbang ke barat terdorong angin dari timur.
Ketika sadar apa yang terjadi, penduduk, Dusun Kinahrejo itu pun ambil langkah seribu pergi meninggalkan tempat itu dan keranjang rumputnya.
"Begitu saya sadar kalau itu wedhus gembel, saya langsung lari. Setiba di rumah saya tidak bisa ngomong apa-apa. Badan saya lemes ..." kata Supiyem di tengah kerumunan pengungsi lain di barak pengungsian, mengisahkan kembali peristiwa yang konon sering dialami penduduk sebelumnya.
Rupanya, hampir bersamaan dengan peristiwa yang dialaminya, di tempat lain terjadi musibah.
Dusun Turgo yang terletak di sebelah barat Dusun Kinahrejo, tempat tinggal Supiyem, dilanda awan panas alias glowing cloud atau beken dengan istilah lokal wedhus gembel.
Puluhan penduduk tewas, hilang, dan terluka parah. Rumah-rumah roboh, pohon-pohon meranggas, sementara lalat-lalat beterbangan menari-nari di atas bangkai ternak-ternak yang mati.
Nganeh-anehi
Penduduk Dusun Turgo, serta beberapa dusun lain yang masuk wilayah Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, tersentak oleh peristiwa itu.
Selama ini sebagian masyarakat di lereng selatan itu percaya, mereka akan selamat dari ancaman meletusnya G. Merapi, meski menghuni areal yang menurut Kantor Seksi Penyelidikan Gunung Merapi merupakan daerah terlarang.
Konon, selama G. Turgo di belakang dusun-dusun itu masih berdiri, mereka percaya bakal aman-aman saja.
Lelehan lava pijar mustahil menerjang kawasan itu. G. Turgo yang hanya beberapa kilometer sebelah barat daya puncak Merapi itu mereka yakini sebagai benteng terhadap ancaman Merapi.
Posisi geografis yang dianggap aman ini masih diperkuat lagi dengan dongeng maupun mitos yang berkembang turun-temurundan kuat diyakini kebenarannya.
Menurut dongeng itu, G. Turgo (1.205 m dpl) dianggap lebih tua dari Merapi. la diyakini sebagai "biyung bibi" (tante) yang mengasuh Merapi sejak kecil.
"Mana mungkin kotoran (lava - Red.) sang kemenakan melangkahi bibinya sendiri. Itu kualat ... akan kualat dan terkutuk," kata Arjo Sutrisno (74).
"Nganeh-anehi sanget (sangat aneh) ..." ujar F.X. Suwadji, Kepala Dusun Turgo, di barak pengungsian Purwobinangun, Pakem, Slerhan, Yogyakarta.
Dalam sejarahnya, katanya, baru kali ini warganya tertimpa bencana. Sepanjang pengetahuannya, lava pijar dan wedhus gembel belum pernah mengarah ke dusunnya.
"Selama ini selalu ke barat," tambahnya.
"Biasanya, kalau Eyang Merapi itu 'kencing' atau 'buang hajat', kami pasti diberi tahu dulu," ujar Warto Utomo' (70), warga Dusun Turgo, yang bersama 4 anak dan 12 cucunya ikut mengungsi di barak Purwobinangun.
Kini, "Eyang Merapi telah berani melangkahi biyung bibi-nya sendiri. Apakah ini semacam peringatan buat kami untuk berlaku kebajikan?" kata si kakek.
Mitos induk
Alam pikiran tradisional masyarakat sekitar lereng Merapi memang sarat dengan mitos, dongeng, atau legenda yang beraneka nuansa dan versi.
Semua itu konon berkembang dan bersumber dari sebuah mitos induk Empu Rama dan Empu Permadi.
Alkisah, ketika diciptakan oleh para dewa, Pulau Jawa dalam keadaan tidak seimbang.
Oleng ke barat karena beban berat Gunung Jamurdipo. Guna menyeimbangkan keadaan, Dewa Krincingwesi berniat memindahkan gunung tersebut ke pusat pulau.
Tapi niat itu teralang oleh kegiatan dua orang empu bersaudara, Empu Rama dan Empu Permadi, yang sedang membuat keris pusaka di tengah-tengah pulau.
Para dewa meminta agar kesibukan membuat keris itu digeser, karena di tempat itu akan diletakkan Gunung Jamurdipo.
Kedua empu ngotot menolak. Alasannya, keris pusaka Pulau Jawa itu hampir selesai dibuat.
Kontan Dewa Krincingwesi naik darah. Di angkatlah pucuk Gunung Jamurdipo lalu dilemparkan tepat ke lokasi kedua empu tadi.
Empu Rama dan Empu Permadi pun terkubur mati.
Untuk memperingati peristiwa itu, patahan pucuk Gunung Jamurdipo yang terlempar itu diberilah nama Gunung Merapi. Artinya, tempat perapian kedua empu.
Lantas Gunung Merapi diyakini sebagai keraton makhluk halus dengan rajanya roh Empu Rama dan Empu Permadi.
Roh keduanya oleh masyarakat setempat disebut Eyang Merapi. Dari mitos induk inilah muncul berbagai varian dan tafsiran baru oleh masyarakat lokal pada setiap zamannya.
Varian mitos perihal Gunung Merapi ini barangkali puluhan jumlahnya.
Sebab masyarakat di hampir setiap sudut lerengnya memiliki mitosnya sendiri sebagai bagian dari sistem keyakinannya entah dalam bentuk persepsi alam murni ataupun alam adikodrati atas gunung itu.
Kandungan salah satu mitos itu antara lain, bahwa korban letusan memang terpilih untuk dijadikan abdi dalem Keraton Merapi.
Atau sebaliknya, akibat keserakahannya sendiri semasa hidupnya.
Dalam mitos itu pula sebagian masyarakat lereng selatan Merapi percaya, jika mereka berbuat kebajikan, makhluk halus penjaga gunung akan melindungi dari segala bencana.
Perlindungan itu biasanya berupa pemberitahuan terlebih dulu sebelum gunung meletus hingga bisa menyelamatkan diri.
Lewat isyarat atau wangsit yang didapat dari mimpi: bisa berujud orang tua berjubah atau berupa gejala alam seperti suara bergemuruh, tanah bergetar, atau turunnya hewan-hewan liar.
Poros Merapi-Keraton Yogya-Laut Kidul
Mitos tentang Gunung Merapi kemudian diuji. Dari kacamata penduduk lereng Merapi yang percaya, Eyang Merapi mblenjani janji.
Apakah Eyang Merapi melupakan janji yang dulu pernah diucapkan kepada Panembahan Senopati pendiri Mataram, seperti tersirat dalam mitos Endhog Sapu Jagad, yakni tidak akan menimpakan bencana kepada rakyat Mataram?
Mengapa pula Eyang Merapi tidak memberi isyarat terlebih dulu kepada penduduk agar bisa menyelamatkan diri?
Oleh karena itu pada malam Jumat Kliwon, 2 Desember 1994, Marijan bersama tetua warga Dusun Kinahrejo mengadakan upacara selamatan dan tirakatan.
Tujuannya supaya warga, khususnya masyarakat lereng Merapi, yang masih hidup diberi keselamatan.
Upacara selamatan itu juga dipakai oleh warga dusun Kinahrejo dan sekitamya agar tetap diperbolehkan bermukim di tanah kelahirannya.
Persepsi Gunung Merapi sebagai keraton makhluk halus tak bisa dilepaskan dari mitos Endhog Sapu Jagad.
Di sana tersirat hubungan antara Keraton Mataram, Keraton Laut Kidul, dan Keraton Merapi.
Ketiga keraton itu, menurut M.M. Sukarto K. Atmodjo, memiliki hubungan mistis dan adikodrati, yang menjamin ketenteraman bagi keberlangsungan raja dan kerajaan beserta seluruh rakyatnya.
"Gunung itu lambang lelaki, laut simbol perempuan. Persatuan keduanya mutlak mirip konsep lingga - yoni, yakni sangkan paraning dumadi," ujar Sukarto yang pakar sejarah Jawa kuno.
Kalau Kanjeng Ratu Kidul adalah penguasa lautan (di selatan), Sapu Jagad adalah penguasa gunung (di utara), maka Panembahan Senopati sebagai penguasa di dataran (Kerajaan Mataram) merupakan simpul penghubung keharmonisan atas keduanya.
Di samping itu kekuatan Mataram tergantung pada dua itu. Itu sebabnya Keraton Yogyakarta setiap tahun menyelenggarakan upacara labuhan.
Hubungan kekeluargaan antara ketiga keraton itu antara lain tercermin pada kepercayaan masyarakat di sepanjang Kali Opak.
Kedua sungai yang bermata air di Gunung Merapi ini dipercaya sebagai jalan utama kunjungan kekeluargaan antara penghuni Laut Kidul dan Gunung Merapi.
Lampor yang dibarengi suara gemerincing di malam hari, diyakini sebagai barisan makhluk halus berkereta kuda pimpinan Kanjeng Ratu Kidul yang hendak kembali pulang dari kunjungannya ke Merapi, menyusuri Kali Opak.
Sabuk gunung dan Laut Kidul
Seperti dituturkan Dr. Sukarto K. Atmodjo, epigraf dan pakar sejarah Jawa kuno dari UGM, Gunung Merapi dan Laut Kidul (Samudera Indonesia) memiliki hubungan mistis dalam mitologinya.
Tapi di luar itu sebenarnya Merapi dan Samudera Indonesia punya kaitan sangat erat dari kacamata geologi.
Apakah kedua fakta ini bersumber dari satu fenomena yang sama atau hanya kebetulan, tidak mudah dijawab.
Yang terang, hubungan antara Merapi - yang menjulang di perbatasan Propinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah – dan Samudera Indonesia ini bisa dijelaskan secara geologis.
Menurut Bambang Widjaja H., seorang geolog dari Jurusan Vulkanologi, Fak. Teknik Geologi, UGM, hubungan itu bisa dijelaskan dengan teori tektonik lempeng.
Kerak bumi yang menyusun dunia ini tersusun dari 12 lempeng besar dan lempeng-lempeng kecil, dengan ketebalan yang bervariasi.
Lempeng-lempeng kerak bumi itu antara lain Lempeng Pasifik, Lempeng Filipina, Lempeng Eurasia (Eropa-Asia), dan Lempeng Samudera Hindia.
Lempeng-lempeng itu saling bergerak relatif satu terhadap yang lain dengan kecepatan 1 - 13 cm per tahun.
Begitupun Lempeng Samudera Hindia, yang merupakan lempeng atau kerak samudera, bergerak secara relatif ke utara terhadap Lempeng Eurasia yang merupakan kerak benua, dengan kecepatan rata-rata 2 cm per tahun.
"Karena densitas atau kerapatan massanya lebih tinggi dari kerak benua, maka kerak Samudera Hindia itu menyusup ke bawah kerak benua Eurasia," kata Bambang Widjaja H.
Di daerah subduction (penyusupan atau penunjaman) antara lempeng Samudera Hindia (Indonesia) dan Lempeng Eurasia itulah terbentuk ring of fire, sabuk atau jajaran gunung api, yang di Indonesia membujur di sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, sampai Laut Banda.
Pulau-pulau ini merupakan bagian dari Lempeng Eurasia. Sedangkan Gunung Merapi merupakan salah satu dari jajaran gunung api itu.
Meskipun nampaknya kecepatan 2 cm per tahun itu lambat untuk ukuran manusia, tumbukan antara massa kerak samudera dan kerak benua itu menimbulkan akibat yang dahsyat.
Selain secara insidental menghasilkan aktivitas kegempaan, gesekan kedua massa raksasa itu menimbulkan panas hingga melelehkan material kerak samudera maupun kerak benua di daerah penyusupan itu.
"Lelehan material itu berupa larutan silikat atau yang kemudian kita kenal sebagai magma," jelas Bambang.
Sumber atau dapur magma Gunung Merapi itu sendiri terletak kira-kira pada kedalaman 60 - 100 km.
Keluarnya magma ke permukaan bumi akibat tekanan yang tinggi itu lalu dinamai aktivitas vulkanisme atau kegunungapian.
Itulah kira-kira kisah sederhana munculnya sabuk gunung api - di mana Gunung Merapi termasuk di dalamnya – pada jalur sepanjang patahan Pulau Sumatera sampai Laut Banda.
Jangan-jangan legenda yang menghubungkan Gunung Merapi dan Laut Kidul itu bersumber dari gejala alam seperti ini?
(Ditulis oleh B. Soelist/Al. Heru Kustara. Seperti pernah dimuat di Majalah Intisari Januari 1995)
Sumber : Gugurnya Mitos dan Hilangnya Wangsit Saat Laboratorium Alam Gunung Merapi ‘Mengamuk’ - INTISARI