Jejak Penyakit Mematikan Zaman Prasejarah : Dari Fosil Sangiran Hingga Relief Candi Borobudur
Bukti-buktinya tercatat dalam sejumlah artefak. Semisal yang tertinggal pada fosil manusia purba di Sangiran, atau relief yang ada di Candi Borobudur.
Penulis: Setya Krisna Sumargo | Editor: Mona Kriesdinar
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Jejak wabah penyakit mematikan diyakini ada sejak masa prasejarah. Secara bergelombang di berbagai peradaban, penyakit yang membunuh ini muncul bergantian.
Bukti-buktinya tercatat dalam sejumlah artefak. Semisal yang tertinggal pada fosil manusia purba di Sangiran, atau relief yang ada di Candi Borobudur.
Di situs purba Sangiran, ditemukan tengkorak Homo erectus yang relatif masih utuh. Di bagian kepalanya ditemukan jejak penyakit, yang diduga karena infeksi.
Sementara di fosil tulang paha manusia Trinil, ada petunjuk terjadi inflamasi otot yang membuat pertumbuhan tulang jadi tidak normal.
“Di bagian parietal kiri dan kanan, ada lesion atau jejak penyakit, mungkin infeksi atau apa, masih belum begitu jelas,” kata Sofwan Noerwidi.
Demikian paparan peneliti Balai Arkeologi Yogyakarta yang sedang menimba ilmu paleontologi prasejarah di Paris, Prancis, Selasa (21/4/2020) sore.
Presentasi dilakukan jarak jauh via aplikasi Zoom, dan ditayangkan secara langsung via akun You Tube Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas).
Sofwan Noerwidi mengirimkan makalah pendek yang dipresentasikannya, ke Tribunjogja.com.
Ia mengizinkan publikasi atas materi tersebut, selain perbincangan virtual yang berlangsung dua jam.
Diskusi dimoderatori Rama Putra Siswantara dari Puslit Arkenas.
Makalah Sofwan diberi judul “Wabah Dalam Sejarah Peradaban Manusia”.
Secara kronologis, Sofwan memaparkan periodisasi zaman, jejak-jejak wabah yang pernah dibuat atau muncul, serta cara manusia meresponnya.
Secara teknis, jejak masa lalu terkait wabah dan penyakit itu bisa diketahui dari ekofak dan artefak. Lalu lewat prasasti serta relief-relief di candi-candi kuno di Nusantara.
“Fosil prasejarah yang ditemukan di Gua Harimau, Sumatera Selatan, juga pernah ditemukan jejak lesion pada tengkorak. Mungkin akibat TBC atau leprosy (lepra),” kata Sofwan.
Sedikitnya bukti petunjuk dari masa purba ini, membuat misteri apakah penyakit itu berkategori wabah atau hanya dialami sebagian orang waktu itu, menjadi sulit dipastikan.
Di masa berikutnya, ketika masyarakat mulai mengenal gambar, tulisan, semakin banyak jejak yang bisa dibaca pada masa kemudian.
Sejumlah relief di Candi Borobudur, terutama level terbawah bagian Karmawibhangga, menggambarkan bagaimana adegan-adegan terkait penyakit pada masa kuno.
“Ada relief menggambarkan hama tikus yang menyerang tanaman padi. Apakah tikus-tikus itu menyebarkan penyakit, pes misalnya, belum kita ketahui,” kata alumni Arkeologi UGM ini.
Relief lain, kata Sofwan, menggambarkan bagaimana teknik pembuatan obat, pengobatan, dan menangani persalinan berujung kematian.
“Ada ahli obat, mungkin tabib, dukun, sedang meracik obat yang dipanaskan. Ada tukang yang menjaga api, lalu membalurkan ramuan ke bahu dan lain-lain,” jelasnya.
Meski ada relief yang menggambarkan kejadian-kejadian masa lampau seperti di atas, masih belum ada petunjuk signifikan apakah penyakit yang terjadi itu berkategori wabah.
Beberapa jenis penyakit yang muncul dalam berbagai sumber tertulis kuno antara lain bubuhen dan wudunen (bisul).
Ada juga belek dan buler pada organ mata. Gondong, ampang, amis antem, apek, jenis-jenis penyakit kulit. Lalu ada umis (mimisan), humbelen (flu), wudug dan barah (lepra), dan uleren (cacingan).
Kisah berikutnya yang lebih jelas menceritakan terjadinya wabah mematikan, muncul dalam cerita rakyat Calon Arang. Ini kisah berlatar belakang masa pra Kerajaan Kediri.
Menurut Sofwan, dalam kisah Calon Arang diceritakan, ia seorang janda sakit hati, yang ingin membalaskan dendam dengan menyebarkan penyakit mematikan.
“Pagi sakit, sorenya orang mati. Wabah itu dikisahkan sangat mematikan,” kata Sofwan.
Periode berikutnya terjadi di belahan benua lain ketika pasukan Mongol menyerbu Eropa.
Mereka secara tidak sengaja, membawa wabah pes yang disebarkan tikus. “Ini yang kemudian diingat dalam sejarah sebagai black death yang menyapu Eropa,” papar peneliti fosil ‘kingkong” Semedo, Tegal ini.
“Pertanyaan kita, apakah pasukan Tartar yang menyerbu Jawa (targetnya Kartanegara di Singhasari), juga membawa wabah yang sama? Ini belum banyak dikaji,” ujarnya beretorika.
Masuk ke periode selanjutnya abad 16, ketika orang Eropa mulai memasuki Nusantara, mereka membawa wabah cacar. Mulanya di Ternate dan Ambon, lalu menyebar ke berbagai daerah.
“Wabah yang sama yang dibawa orang Eropa, menghancurkan para penduduk asli Amerika dan Amerika Utara,” lanjutnya.
Lalu di masa Mataram Islam, Sultan Agung pernah dua kali menciptakan wabah untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya.
Pertama ketika mengepung dan menaklukkan Surabaya. Pasukan Sultan Agung membendung Kali Mas, memasukkan bangkai dan aren, menyebarkan bakteri serta kuman yang membuat kadipaten itu takluk.
Usaha kedua dilakukan Sultan Agung saat hendak menaklukkan kota VOC di Batavia 1628. Tekniknya sama seperti di Surabaya, pasukannya membendung Kali Ciliwung.
Tapi usaha itu gagal karena Batavia ternyata memiliki sistem cadangan air sumur dan artetis, sehingga penduduk kota benteng Batavia terhindar dari penyakit kolera yang mematikan.
Namun Gubernur Jan Pieterzen Coen akhirnya dikabarkan meninggal akibat kolera, selama masa pengepungan dan usaha penaklukan Batavia oleh raja Jawa itu.
Cara serupa, menciptakan wabah untuk menaklukkan musuh, terjadi saat perang Makassar 1668.
Pasukan VOC dan Bugis banyak yang tewas karena penyakit yang diderita selama peperangan.
Abad 18 diwarnai dua kejadian besar, pandemic kolera dan pes. Diawali letusan gunung Tambora yang super dahsyat 1815, terjadi “importasi” beras dari India.
Beras itu ternyata terkontaminasi bakteri kolera dari delta Gangga, tiba di Jawa, lalu menyebar ke berbagai tempat.
Wabah kolera juga terjadi saat perang Paderi di Tapanuli dan perang Jawa (1825-1830). Pandemi kedua adalah pes yang diduga berasal dari Yunnan, Tiongkok.
Wabah ini melintasi dunia selama beberapa dekade selanjutnya, menyapu sebagian penduduk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten.
Awal abad 20 menurut Sofwan Noerwidi, tikus-tikus pembawa pes menyebar lewat kapal-kapal uap ke enam benua, menyebarkan maut di berbagai tempat.
Secara mendasar, menurut Sofwan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan wabah itu begitu cepat tersebar jadi pandemik.
“Ada perubahan lingkungan, bencana, serta migrasi hewan carier,” katanya.
Faktor kedua jaringan perdagangan, pelayaran kapal, serta munculnya jalur sutra serta rempah-rempah.
“Faktor ketiga, pola hidup tidak sehat, permukiman padat dan kumuh. Selanjutnya akibat perang/konflik dan keberadaan korban yang terbengkelai,” beber Sofwan.
Sebab lain, kata peneliti yang kini menekuni paleontologi prasejarah, akibat wabah artifisial atau buatan. “Contohnya ya aksi pasukan Sultan Agung di Surabaya dan Batavia,” ujarnya.
Menghadapi peristiwa itu, secara naluriah orang-orang kuno atau masa lalu meresponnya secara naluriah.
Ada yang mengisolasi diri di lingkungan tempat tinggalnya, ketika ada wabah di tempat lain. “Atau bermigrasi alias pindah hunian karena yang lama tercemar,” jelas Sofwan.
Sisi lain, kemunculan wabah itu membuat masyarakat berinisiatif membuat obat, menata lingkungan, berpola hidup sehat, dan lebih religius.
Sementara I Gede Wiratmaja Karang, dalang dan praktisi pengobatan asal Bangli, Bali, menjelaskan wabah di khasanah sejarah Bali dikenal sebagai “sasab” atau grubug.
Ia merujuk prasasti Pura Kehen di Bangli yang menyebut pada masa kuno pernah terjadi sasab atau wabah mematikan di Bangli.
“Banyak penduduk meninggal dunia,” kata Gede Karang, yang memaparkan secara daring di diskusi yang dihelat Puslit Arkenas.
Masyarakat Bali menurutnya memiliki ketahanan tersendiri, perpaduan antara tradisi, budaya, dan tuntutan keagamaan yang sangat kuat.
Menurutnya ada tiga unsur penting yang menentukan apakah orang itu sehat atau sakit. Yaitu unsur Vatta (udara), Pitta (api), dan Kapha (air), serta ditambah unsur tanah.
Dalam lontar Usadha, ketiga unsur itu disebut tri dosha. Mengenai istilah sasab, Gede Karang menjelaskan, secara bahasa Sanskrit, sasab artinya tutup, selimut.
Intrepretasinya, penyakit yang muncul itu penuh rahasia, sebabnya tidak diketahui secara akal, pengobatannya pun sangat rahasia dan tertutup.
Gede Karang menekankan, dalam kultur Bali, ada prinsip manusia disebut sehat jika semua sistem dan unsur pembentuk tubuh yang disebut Panca Maha Bhuta, serta cairan tubuhnya seimbang.
Cara meresponnya, selain menggunakan pengobatan yang dilakukan balian atau sekarang dokter, biasanya juga ada local genius menggunakan ramuan khusus sebagai tolak bala atau jimat.
“Bali hingga hari ini kabarnya belum ada korban meninggal akibat Covid-19, kecuali dua orang itu warga asing,” kata Gede Karang.(Tribunjogja.com/xna)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/ilustrasi-manusia-purba_20180426_152148.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/presiden-jokowi-blak-blakan-soal-alasannya-memilih-tito-karnavian-jadi-menteri-dalam-negeri.jpg)



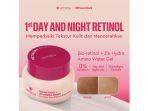




![[FULL] Isi Pidato Gibran di Penutupan KTT G20, Tangan sampai Tunjuk-tunjuk & Banjir Tepuk Tangan](https://img.youtube.com/vi/hvJOOsDh9VU/mqdefault.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Ketum-PBNU-Gus-Yahya-saat-diwawancara-awak-media-23122023.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Trump-dan-Zohran-Akhirnya-Berdamai.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Kronologi-Pesawat-GA8-Airvan-Nyungsep-di-Areal-Persawahan-Karawang.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Hamper-untuk-Hari-Guru.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Konsolidasi-di-Kota-Yogya-Partai-Gelora-Tekankan-Politik-Narasi-Menyasar-Gen-Z.jpg)